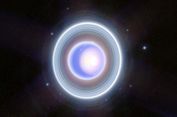Pemberitaan Reynhard Sinaga, Maukah Kita Membayar untuk Jurnalisme Berkualitas?

Lalu mau apa?
Pastinya, mau model bisnisnya apa pun, praktik jurnalisme yang buruk tidak bisa diterima. Jangankan pembaca, wartawan juga malas kalau ada rekan satu redaksi yang membuat berita buruk.
Tak terhitung perdebatan di grup WhatsApp bersama rekan kerja maupun atasan untuk mengupayakan jurnalisme yang berkualitas.
Kritik dari pembaca, seperti pada kasus Reynhard, penting dan perlu. Namun lebih dari itu, perlu upaya kolektif sehingga jurnalisme yang baik itu bukan menjadi mimpi.
Di sini, kemauan media untuk bereksperimen penting. Demikian juga kemauan publik untuk berkontribusi serta akademisi dan peneliti media untuk melihat lebih dalam.
Di Inggris, ada The Bristol Cable yang bereksperimen dengan model koperasi. Anggota koperasi adalah pemilik media.
Dengan ini, maka suara anggota yang punya ragam latar belakang bisa didengar. Hingga tahun 2018, sebagian besar pendanaan media ini masih bersumber dari grant.
Namun, salah satu reporter media itu bernama Matty Edwards mengungkapkan, The Bristol Cable akan meningkatkan jumlah anggota dan berharap kontribusi keuangan dari mereka untuk beroperasi.
Media dari Swiss, Republik, juga punya model yang mirip. Dalam 7 jam peluncuran, media ini mendapat 3.000 subscriber dan sekitar Rp 10 miliar.
Republik bukan mengajak orang membeli artikel, tetapi membayar untuk menjadi bagian dari komunitas dan memperjuangkan kebenaran bersama. Salah satu jargon media ini adalah "No Journalism, No Democracy".
Di Indonesia belum ada model ini. Sejumlah media mengupayakan model subscription. Namun, harian Kompas lewat Kompas.id misalnya, dengan 275 juta penduduk Indonesia, masih terus berjuang untuk meningkatkan subscriber-nya.
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, ada beberapa media baru muncul dengan bantuan donor tetapi banyak dari mereka surut ketika donor lepas.
Media di Indonesia punya pekerjaan rumah, bagaimana agar orang merasa beritanya worth it sehingga publik mau berkontribusi?
Perlukah ragam tipe subscription? Misalnya, kalau dulu satu kelurahan bisa baca satu koran, mungkin bisa subscription untuk komunitas, keluarga, atau beberapa orang dengan harga berbeda?
Toh, ini juga yang sebenarnya dilakukan Netflix, Spotify, banyak platform berbayar lain.
Sementara itu, peneliti media dan akademisi punya pekerjaan rumah juga untuk menjawab lebih dari soal bagaimana media mem-framing sebuah kasus.
Analisis untuk menjawab "mengapa begitu?' dan "bagaimana agar tidak begitu?" perlu dilakukan dengan banyak pisau. Bukan hanya dari kacamata komunikasi dan jurnalisme, tapi juga bisnis, teknologi informasi, dan lainnya.
Di Inggris, ada Reuters Institute for the Study of Journalism yang mempertemukan jurnalis, peneliti, dan akademisi untuk mengeksplorasi masa depan jurnalisme.
Tiap tahun, institut ini menerbitkan laporan yang misalnya tren dalam jurnalisme. Jadi bukan hanya berkata "media seharusnya... " tetapi memberikan data sebagai acuan media serta mengajak bersama mencari solusi.
Nah untuk pembaca, apa iya berita harus selamanya gratis? Kenyataannya, jurnalisme ada cost-nya.
Bukan hanya finansial, tetapi mungkin juga nyawa. Contohnya kasus kolumnis dan jurnalis Jamal Khassogi.
Jika bisa membeli rokok yang memicu kanker paru, bubble tea yang bisa memicu kegemukan, maka harusnya Anda juga bisa berkontribusi untuk jurnalisme yang sangat boleh jadi penting untuk kepentingan Anda sendiri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.-
![]() Apa Itu Obat GHB, Rape Drug yang Digunakan Reynhard Sinaga?
Apa Itu Obat GHB, Rape Drug yang Digunakan Reynhard Sinaga? -
![]() Reynhard Sinaga Disebut Psikopat, Apa Bedanya dengan Sosiopat?
Reynhard Sinaga Disebut Psikopat, Apa Bedanya dengan Sosiopat? -
![]() Kasus Reynhard Sinaga, Psikiater: Ada Penyimpangan Perilaku Seksual
Kasus Reynhard Sinaga, Psikiater: Ada Penyimpangan Perilaku Seksual -
![]() Kasus Reynhard Sinaga, Ini Tes untuk Tahu Anda Psikopat atau Tidak
Kasus Reynhard Sinaga, Ini Tes untuk Tahu Anda Psikopat atau Tidak -
![]() Tampan, Pintar dan Kaya: Mengapa Reynhard Sinaga Melakukan Pemerkosaan?
Tampan, Pintar dan Kaya: Mengapa Reynhard Sinaga Melakukan Pemerkosaan? -
![]() Lewat Kasus Reynhard Sinaga, Membayangkan Trauma Korban Pemerkosaan
Lewat Kasus Reynhard Sinaga, Membayangkan Trauma Korban Pemerkosaan