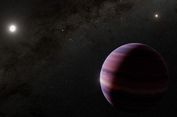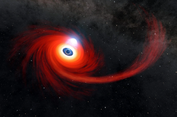Wabah Virus Corona, Tamparan Pahit Kesehatan Manusia dari Krisis Iklim
Oleh Niel Makinuddin dan Dianing Sari
Hanya dalam hitungan bulan, virus corona Wuhan atau SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19 sudah menghambat pertumbuhan ekonomi dunia.
Namun, di luar dari jumlah korban yang terus bertambah, epidemik yang terus meluas (tersebar di 64 negara hingga 2 Maret 2020), muncul sejumlah analisis tentang efek krisis atau darurat iklim dengan masifnya penyebaran virus corona.
Untuk diketahui, krisis iklim merupakan kondisi yang dideklarasikan 11.000 ilmuwan dunia pada November 2019, karena bumi sudah dalam kondisi darurat, bukan lagi perubahan iklim.
Kata darurat iklim ini juga menjadi "word of the year 2019" (kata tahun 2019) dari kamus Oxford yang didefinisikan sebagai kondisi mendesak yang membutuhkan aksi untuk mengurangi atau menahan perubahan iklim dan mencegah kerusakan lingkungan yang tak bisa diperbarui akibat perubahan iklim tersebut.
Dampak perubahan iklim adalah ancaman nyata, tidak hanya dari bencana, kenaikan suhu, melainkan juga kesehatan manusia.
Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah merilis sebuah laporan panjang berjudul "Climate Change and Human Health - Risks and Responses" pada 2003 silam.
Laporan sebanyak 38 halaman, tersebut menyatakan bahwa perubahan iklim akan berdampak pada : a) mereka yang terpapar langsung dari perubahan cuaca ekstrem; b) mereka yang kesehatannya terdampak dari kondisi lingkungan yang secara bertahap memburuk akibat perubahan iklim; c) konsekuensi ganguan kesehatan yang beragam (trauma, penyakit menular, kekurangan gizi, gangguan psikologis, dan lain-lain), akibat dislokasi populasi dari perubahan iklim.
Pada pilihan yang terakhir, Badan Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa pola transmisi penyakit menular sangat dipengaruhi perubahan iklim.
Contohnya adalah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui vektor, yang secara bersama-sama dipengaruhi oleh kondisi iklim, pergerakan populasi, pembukaan hutan dan pola penggunaan lahan, hilangnya keanekaragaman hayati (misalnya : predator alami nyamuk), konfigurasi permukaan air tawar, dan kepadatan populasi manusia.
Lalu, bagaimana kasus virus corona?
Profesor Mikrobiologi dari Johns Hopkins University’s Bloomberg School of Public Health Arturo Casadevall menyatakan bahwa setiap kejadian adanya hari sangat panas di bumi, manusia mengalami suatu peristiwa besar.
Profesor Arturo menjelaskan bahwa patogen (bakteri, virus, dan jamur yang menimbulkan penyakit) bisa bertahan, berkembang biak, dan beradaptasi lebih baik pada suhu yang menghangat, termasuk di suhu tubuh manusia.
Tahun ini, suhu di Antartika memecahkan rekor tertinggi di angka 18 derajat celcius, yang terjadi pada 6 Februari 2020. Kenaikan suhu di Antartika dan melelehnya lapisan es di kutub utara tersebut adalah tanda nyata dari krisis iklim yang bisa dilihat dengan kasat mata.
Bagaimana mencairnya es di dari kutub utara menuju ke penyebaran virus atau penyakit menular? Benang merahnya adalah si pembawa sumber penyakit.
Dr. Tracey Goldsten dalam laporan bertajuk "The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate", pada September 2019 lalu menyatakan bahwa hilangnya lapisan es di Kutub Utara mendorong satwa laut liar di dalamnya untuk bermigrasi.
Lantas, dalam proses migrasinya mencari tempat makan dan tempat tinggal baru, mereka akan berinteraksi dengan satwa yang sebelumnya tidak sehabitat.
“Interaksi beda habitat ini membuka peluang dalam perkenalan dan transmisi penyakit menular baru, yang sayangnya berpotensi mematikan,” ujar Tracey yang juga peneliti dari Universitas California, Davis.
Sejarah sudah mencatat, bahwa hewan adalah pembawa patogen ke manusia. Mulai dari awal 1980, bagaimana AIDS/HIV yang banyak terindikasi menyebar dari monyet, lalu flu burung di pertengahan tahun 2000-an, diikuti flu babi di akhir 2000-an.
Teranyar, mengutip tulisan Profesor Tim Benton yang dimuat situs berita BBC pada 31 Januari 2020, kelelawar menjadi induk penyebaran corona virus dan turunannya (SARS, MERS dan Covid-19) dan sebelumnya diketahui bahwa kelelawar juga memberi manusia pandemik Ebola di Afrika.
Profesor Tim yang juga Direktur Program Energy, Environment and Resources di Royal Institute of International Affairs, dengan terang menyatakan bahwa manusia selalu mendapatkan penyakit dari hewan (zoonosis). Bahkan, hampir semua penyakit menular penyebaran dari satwa liar.
Namun, krisis iklim yang semakin parah, mempercepat prosesnya. Apalagi globalisasi membuka ruang manusia untuk berpindah tempat dalam waktu cepat.
Nah, sayangnya, pada kasus penyebaran penyakit hewan ke manusia, Profesor Tim menguraikan korban paling rentannya adalah penduduk di wilayah padat dan miskin.
Mereka yang hidup dalam tempat dengan sanitasi buruk, udara yang terpolusi, dan nutrisi kurang, akan menyebabkan imun tubuh melemah, sehingga membuka ruang untuk masuknya patogen. Padatnya populasi kota, juga mempercepat penyakit menular ini.
Pendapat dari Profesor Tim tersebut dikuatkan sejawatnya dari Global Change Center, Virginia Tech, yaitu Dr. Luis Escobar.
Dalam wawancara dengan radio WVTF (radio nasional di kawasan Virginia, Amerika Serikat) pada 6 Februari lalu, Luis menyatakan bahwa krisis iklim membuka benteng manusia terhadap patogen.
Secara spesifik, ahli penyakit ekologi ini, menjelaskan bahwa deforestasi dan pembukaan tutupan hutan akan mendekatkan manusia dengan virus yang seharusnya hidup di habitat liarnya.
Doktor Luis mengatakan, sedari ribuan tahun lalu virus-virus ini sudah hidup berdampingan dengan manusia dan hewan. Virus ini berinang ke hewan-hewan liar tersebut. Namun kenaikan suhu bumi dan perilaku manusia yang merusak alam, mengubah ekosistem dan perilaku para satwa ini. Satwa pun bermigrasi atau bahkan berinteraksi dengan manusia.
Padahal, menurut Luis, satwa liar dan virus itu sudah berevolusi bersama sampai ke tingkat tidak membahayakan bagi alam. Virus membutuhkan inang, untuk tetap hidup dari generasi ke generasi dan bisa hidup tanpa membuat hewan yang ditempatinya sakit.
Namun, ketika iklim dan bentang alam habitat induknya berubah, virus pun mengalami adaptasi. Virus flu, Luis mencontohkan, lebih mudah bertahan di udara yang lembap, ketimbang udara kering. Fakta ini menunjukkan bahwa iklim akan mempengaruhi kecepatan penyebaran virus.
Pada kasus corona, dia menemukan bahwa virusnya lebih cepat menyebar, ketimbang dua kakaknya dahulu, yaitu SARS dan MERS.
Korelasi antara kenaikan suhu bumi dengan kecepatan penyebaran penyakit berbasis virus dari induk kelelawar, memang belum ada data ilmiah yang disepakati bersama. Namun, pada kasus arboviral (infeksi virus dari serangga dan artopoda), sudah ada kajiannya tentang korelasi perubahan iklim.
Dalam laporan WHO di atas, disebutkan bahwa kenaikan suhu 2-3 derajat celcius, akan meningkatkan terjadinya demam berdarah dan malaria 3-5 persen.
Peneliti dari Universitas Florida, menguatkan estimasi WHO tersebut. Laporan di jurnal PNAS berjudul "Amazon deforestation drives malaria transmission, and malaria burden reduces forest clearing" yang terbit Oktober 2019 menunjukkan bahwa korelasi kuat antara pembukaan tutupan hutan tropis dan penyebaran penyakit.
Tim peneliti dari Universitas Florida menyimpulkan bahwa kenaikan laju deforestasi di Hutan Amazon, Brasil sebesar 10 persen, akan mendorong peningkatan kasus malaria sebesar 3.4 persen.
Jadi, apakah kita masih mau menjadi penonton atau terjun langsung dalam ikhtiar mencegah darurat iklim? Corona dan darurat iklim menanti aksi nyata kita.
Niel Makinuddin dan Dianing Sari
Pegiat lingkungan di Yayasan Konservasi Alam Nusantara/YKAN)
Catatan penulis: opini ini tidak mewakili pandangan YKAN
https://sains.kompas.com/read/2020/03/02/120300523/wabah-virus-corona-tamparan-pahit-kesehatan-manusia-dari-krisis-iklim