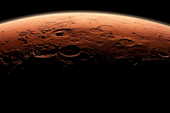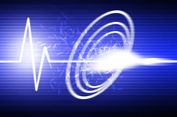Nasionalisme Bukan Sekadar Pakai Batik
Tidak mengagetkan sebetulnya, karena seperti yang kerap saya bilang ke pasien, semua pesawat dilengkapi kokpit dan semua pertandingan olah raga punya papan skor. Baik kokpit maupun papan skor sama-sama mempersiapkan kita untuk mendarat mulus, meraih medali emas atau kebalikannya.
Begitupun setumpuk pekerjaan rumah dengan sampul gizi kurang dan gizi buruk sudah bisa diprediksi sekian tahun yang lalu.
Tak perlu kaget juga jika Presiden kita jadi sengit menyoal anak-anak yang masih saja didera gangguan gizi, sementara sepertiga penghasilan para ayahnya disambar pabrik rokok.
Beliau boleh berang dan menginginkan agar kondisi ini harus dihentikan segera, tapi situasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Apalagi, jika disejajarkan dengan ketahanan maritim kita saat menteri kelautan dan perikanan dengan patriotisme tinggi siap meledakkan kapal-kapal asing.
Yang kita hadapi di dunia kesehatan bukanlah orang asing. Melainkan anak-anak negeri yang pola makannya selama sekian puluh tahun sudah bergeser seperti orang asing.
Di pemukiman padat penduduk maupun di pesisir atau pelosok desa, anak-anak diberi makan roti, susu (baca: susu kental manis yang diencerkan, pokoknya bangga bisa minum susu), sosis, mi instan dan baso warung.
Ada ibu yang berlinang air mata mengatakan, pernah makan singkong rebus karena tidak punya beras lagi. Baginya, makan singkong adalah mimpi buruk kemiskinan.
Sekian puluh tahun paradigma gizi sehat diproyeksikan ke hitung menghitung kalori dengan mahzab klasik.
Bahkan, sampai ada yang tega-teganya membuat campuran aneh terbuat dari minyak kelapa ditambah berbagai macam tepung untuk dikocok dan disebutnya sebagai formula pendongkrak gizi.
Seakan-akan yang diberi makan itu ayam potong yang bila sudah gemuk timbangannya, lalu ditinggal dan tahu-tahu sekian tahun kemudian bisa mendadak makan sayur dan buah serta jadi juara kelas. Kok rasanya ada yang enggak nyambung, ya?
Makanan oraktis dan efisien bukan jawaban perbaikan gizi
Gizi dan pola makan perlu diteropong dengan teleskop multi faset. Jika tidak mau kebablasan seperti yang kita alami saat ini.
Tumbuh kembang anak tidak melulu soal kecukupan kalori dan teori keseimbangan karbohidrat protein dan lemak.
Pola asuh bukan sekedar perkara menyuapi anak dengan sabar dan mendongeng tiap malam. Semua itu berhubungan dengan pemahaman kodrat, kebiasaan, kebutuhan, dan tentunya kecanduan.
Kodrat bicara tentang hukum alam yang tak mungkin bisa digantikan dengan hukum teknologi. Jadi, kacau sekali bila istilah ‘praktis dan efisien’ diterapkan pada perbaikan gizi dan makanan yang diharapkan membereskan masalah gizi.
Pola asuh atas nama kepraktisan sudah merusak hampir di semua lapisan masyarakat kita. Didukung oleh para pakar yang bekerja demi industri pula.
Dengan tetap mengandaikan rakyat bodoh dan jorok, maka memberi makanan dari kemasan dianggap lebih menjamin kebersihan dan ketepatan gizinya – dibanding menyiapkan pangan yang sesuai kodrat dan martabat: mulai makan dari hasil kebun hingga menikmati hasil tangkapan.
Alhasil kekayaan kebun, ternak hingga tangkapan justru menjadi komoditas untuk ditukar dengan uang. Dan uangnya dibelikan “makanan” non kodrati yang ‘sesuai dengan daftar komposisi’ di bungkusnya.
Sangat menyedihkan mendengar permintaan para orangtua anak-anak bergizi kurang, agar mereka diberi bantuan makanan instan dan susu – dengan preferensi sesuai lidah anak-anaknya yang sudah terlanjur kecanduan rasa artifisial dan manis.
Mereka tidak bisa dipersalahkan, karena selama ini uluran tangan model itulah yang mereka nikmati. Dan pihak yang mengulurkan tangan sudah merasa cukup berjasa dengan ‘memberi bantuan’.
Tenaga kesehatan sebagai tombak paling ujung di desa maupun kecamatan juga sudah terbiasa dengan pola demikian.
Seandainya melakukan aksi ‘jemput bola’ pun, mereka hanya bermodalkan obat-obatan sesuai indikasi dan (sekali lagi) ‘bantuan pangan’ yang dikemas dengan cetakan tanggal kadaluwarsa. Mau sampai kapan?
Menjadi berdaya bersama-sama
Revolusi mental membutuhkan terobosan pendekatan. Perubahan paradigma. Pergeseran cara. Tidak mungkin rakyat diajarkan soal preventif dan promotif kalau tidak paham apa itu gaya hidup sehat. Apalagi tidak paham apa itu pangan yang sehat.
Menjadi berdaya, belajar lagi membuat masakan bergizi di rumah, mengalokasikan uang rokok menjadi jatah sayur dan buah, membutuhkan kerja nyata dan contoh mulai dari petinggi hingga pelayan rakyat, alias petugas kesehatan.
Rakyat tidak cukup diberi slogan-slogan ‘awareness’. Apalagi ditakut-takuti dengan gambar.
Alasan kuno petani tembakau bakal jatuh miskin, jika perokok makin sedikit terlalu menggelikan. Kenyataannya, rokok impor liar beriklan mulai dari pasang spanduk hingga banting harga. Indonesia adalah tempat terbaik untuk pemasaran rokok.
Sebetulnya, jika mau inovatif sedikit, negeri ini bisa menjadi produsen satu-satunya pestisida organik berbahan tembakau. Masalahnya, ada yang berpihak pada pabrik rokok. Bukan petani tembakaunya.
Sudah waktunya petugas kesehatan, kader, PKK, para relawan ahli ekonomi, ekologi, pendidikan, pertanian, turun bersama – bukan memberi ceramah – tapi turun tangan menunjukkan bagaimana caranya menyiapkan makanan, menyimpan sisa bahan makanan, mengelola keuangan dalam seminggu, menangani anak yang rewel dan tidak doyan ini itu, memerbaiki ventilasi rumah, mengatur pembuangan limbah dan jamban.
Semuanya hanya bisa terlaksana dibawah koordinasi orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan pendekatan kerakyatan. Saatnya rakyat menjadi tujuan, bukan dijadikan sarana.
Halaman gedung pemerintahan seminggu sekali bisa diikhlaskan menjadi tempat dagang para petani dan nelayan yang tak mampu punya lapak. Mereka menjual dengan harga murah, sesama rakyat yang beli pun menikmati kemurahan harga.
Keterlibatan pengusaha bukan lagi dengan memberi sumbangan makanan sebagai promosi terselubung – tapi membangun infrastruktur.
Apalagi artis, ketimbang disorot mengunyah biskuit gandum – yang bahan bakunya saja tak tumbuh di negri ini - apa salahnya mempromosikan singkong rebus dengan sambal ikan roa?
Tidak berhenti di situ, ajak rakyat melihat manfaat dan hasilnya. Jangan lupa, prinsip perubahan perilaku: orang hanya jadi konsisten dan persisten jika mampu menikmati hasil.
Solidaritas, nasionalisme, tidak cukup hanya berkoar-koar di ruang konferensi apalagi ramai-ramai pamer batik.
Kesetiakawanan nasional hadir saat rakyat menikmati pemberdayaan, bukan pembodohan. Saat kita semua bangga makan nasi jagung, singkong, ubi dan kapurung.
Saat bandara internasional tanah air juga menjual arsik, naniura, hingga lawa mairo – bukan aneka pancake dan lobi penuh asap rokok.
https://sains.kompas.com/read/2017/03/08/090300323/nasionalisme-bukan-sekadar-pakai-batik