Einstein, Zuckerberg, dan Misteri Mentalitas Generasi Medsos

KOMPAS.com – Gelagatnya, Mark Zuckerberg bakal ketularan Albert Einstein, bertanya-tanya kenapa hasil kerja mereka dipakai tak sesuai peruntukan.
Kalau Einstein "meratapi" rumus energinya dipakai untuk membuat bom yang meluluhlantakkan Hiroshima, Zuckerberg boleh jadi mulai bertanya-tanya soal pemanfaatan media sosial besutannya.
Sejak kehadirannya, media sosial telah menjadi kajian tersendiri di ranah psikologi dan sosiologi. Perkembangan dan penggunaan media sosial yang meledak selepas era booming dotcom pada 2000, menghadirkan beragam fenomena yang jauh melampaui ide Zuckerberg.
“Google telah memudahkan orang mencari informasi dan berita, tetapi peranti itu tidak mencukupi untuk mengenal dan atau tahu tentang orang-orang di sekitar kita,” ujar Zuckerberg soal pemikiran awalnya membuat media sosial besutannya, seperti dikutip di Business Insider pada 29 Februari 2016.
Siapa mengira, kini media sosial bukan lagi dipakai untuk saling kenal dan tahu dengan orang-orang sekitar, tapi justru lebih banyak jadi wadah kenarsisan. Aksi pem-bully-an dan penipuan bukan pula satu dua kali terdengar dari keriuhan dunia kekinian ini.
Terkini, penggunaannya bahkan menyimpang sampai menjadi tragedi.
 Ilustrasi ragam media sosial
Ilustrasi ragam media sosialSetidaknya empat peristiwa beda benua, telah mengguncang dunia dalam tiga bulan pertama pada 2017. Tiga peristiwa terjadi di Amerika Serikat, sementara satu peristiwa lain terjadi di Jakarta, Indonesia. Sebelumnya, pada Oktober 2016, tragedi serupa juga terjadi di Turki.
Semua peristiwa itu menyalahgunakan fitur tayangan live di media sosial untuk merekam aksi bunuh diri, yang jelas hanya meninggalkan tragedi. Ironisnya, jejaring sosial milik para pelaku seolah tak berdaya menghentikan aksi itu.
Bahkan, ditengarai banyak orang yang malah menjadikannya tontonan atau sibuk menganggap tayangan itu sebagai rekaman palsu, di samping segelintir dari mereka yang mencoba menghentikan tindakan tersebut.
Pertanyaannya, ada apa dengan mentalitas para pengguna media sosial ini?
Medsos dan indikasi masalah mental
“Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat” adalah frasa yang pernah nge-hits untuk mengkritisi fenomena media sosial.
Setidaknya, itu ungkapan yang beken pas ngetren-ngetrennya media sosial besutan Zuckerberg, beberapa tahun lalu.
Becanda atau tidak, frasa itu kurang lebih mewakili berbagai riset yang menengarai ada persoalan di balik perilaku banyak orang yang asyik-masyuk dengan media sosial.
Tentu, riset ini tak membahas pengguna media sosial yang masih sejalan dengan niat Zuckerberg membuat aplikasinya.
 Hasil survei Litbang Kompas terkait seberapa sering responden mengakses media sosial. Metode survei dilakukan dengan tatap muka yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 14-22 Desember 2015. Sebanyak 1.414 responden warga Jakarta berusia minimal 13 tahun yang dipilih secara acak menggunakan pencuplikan sistematis. Tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin off error penelitian kurang lebih 2,6 persen.
Hasil survei Litbang Kompas terkait seberapa sering responden mengakses media sosial. Metode survei dilakukan dengan tatap muka yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 14-22 Desember 2015. Sebanyak 1.414 responden warga Jakarta berusia minimal 13 tahun yang dipilih secara acak menggunakan pencuplikan sistematis. Tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin off error penelitian kurang lebih 2,6 persen.Igor Pantic, misalnya, dalam riset yang dipublikasikan Badan Kesehatan Amerika Serikat (NIH) pada Oktober 2014, merangkum sejumlah risiko dan gejala masalah kesehatan mental dengan penggunaan berlebihan media sosial.
Di antara gelagat masalah itu mencakup depresi, percaya diri yang rendah, hingga buruknya kualitas tidur pengguna aktif media sosial.
Riset terbaru dari University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences—yang diumumkan pada 19 Desember 2016—bahkan sudah bisa memberi sinyal awal depresi pada pengguna media sosial. Indikator pertama yang dipakai adalah jumlah pemakaian platform media sosial.
Daripada memakai indikator waktu yang dihabiskan untuk berinteraksi di media sosial, riset ini mendapati jumlah penggunaan aktif platform jejaring sosial lebih kuat korelasinya dengan gejala depresi dan kegelisahan bahkan kecemasan berlebihan di kalangan anak muda.
“Kaitan (jumlah platform yang dipakai dengan gejala masalah mental) itu cukup kuat bagi para dokter mempertimbangkan pasiennya menderita depresi dan kegelisahan, untuk lalu memberi mereka konseling,” ungkap Brian A Primack, ketua tim riset ini dalam publikasi tersebut.
Masih ada misteri
Lalu, kapan kita harus mewaspadai diri atau orang lain mulai punya gejala depresi atau kegelisahan terkait penggunaan media sosial?
 Ilustrasi
IlustrasiRiset berbasis survei atas 1.787 orang berusia 19-32 tahun yang aktif media sosial oleh tim Universitas Pittsburg tersebut mendapati, pengguna sekaligus 7-11 platform media sosial punya risiko 3,1 kali lebih besar menderita depresi dan kecemasan dibanding pemakai 0-2 media jejaring sosial pada satu waktu.
Risiko meningkat lagi menjadi 3,3 kali lebih besar untuk penggunaan lebih dari 11 platform media sosial. Temuan dari jumlah pemakaian platform itu tak banyak berubah, sekalipun sudah dibandingkan dan disesuaikan dengan data lama pemakaian media sosial dari setiap responden.
Riset ini menggunakan alat pengukur berupa kuosioner dan peranti penguji standar gejala depresi. Namun, Primack mengakui pula, masih banyak tersisa pertanyaan terkait hubungan antara penggunaan media sosial dan indikasi persoalan kesehatan mental.
Menurut Primack, masih butuh lebih banyak riset untuk bisa menghasilkan kesimpulan lebih jelas soal kaitan antara media sosial dan masalah kesehatan mental.
“Bisa jadi mereka yang punya gejala depresi dan kecemasan—atau keduanya sekaligus—cenderung menggunakan lebih banyak media sosial, untuk mencari perasaan nyaman dan penerimaan. Sebaliknya, bisa juga diartikan, mereka yang benar-benar mencoba mengelola kehadiran di berbagai media sosial ini punya indikasi depresi dan kecemasan,” papar Primack.
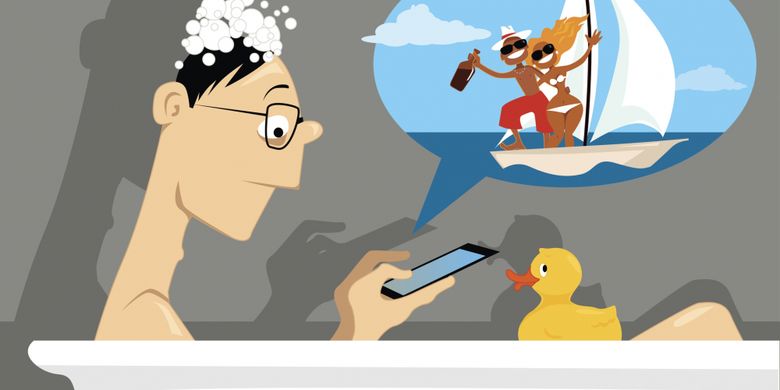 ilustrasi khayalan media sosial
ilustrasi khayalan media sosialPenulis lain dalam riset tersebut, Cesar G Escobar-Viera, menambahkan, memahami cara dan pengalaman pemakai pengguna media sosial akan menjadi tahapan kritis dalam riset berikutnya, selain upaya mencari tipe spesifik gejala depresi dan kecemasan terkait penggunaan jejaring sosial.
“Yang terpenting, kami ingin riset ini membantu upaya perancangan dan penerapan intervensi edukatif soal kesehatan publik untuk kebutuhan yang personal sekalipun,” imbuh Escobar-Viera.
Menagih peduli
Zuckerberg dan kru-nya pun tak tinggal diam menyikapi fenomena pemanfaatan melenceng dari platform besutan mereka.
Seperti diberitakan Kompas.com, Kamis (2/3/2017), Facebook sudah menyiapkan peranti berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) untuk menyaring gejala bunuh diri atau penyakit mental seperti depresi dari postingan para penggunanya.
Sistem tersebut antara lain akan menyortir unggahan seperti kekhawatiran terhadap perilaku seseorang. Product Manager Facebook Vanessa Callison-Burchold mengatakan, AI ini sudah mulai diujicobakan di Amerika Serikat.
Menurut Callison-Burchold, hasil yang didapat lebih akurat dibandingkan dibandingkan laporan dari sesama pengguna.
 Surat Mark Zuckerberg tentang pencegahan penyalahgunaan media sosial
Surat Mark Zuckerberg tentang pencegahan penyalahgunaan media sosial"Kemungkinannya lebih besar bagi Facebook untuk mengirim sumber daya (pencegah bunuh diri) ke orang-orang yang dilaporkan oleh AI, ketimbang yang dilaporkan oleh pengguna," ujar Callison-Burchold, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Buzzfeed, Kamis (2/3/2017).
AI, lanjut Callison-Burchold akan bekerja otomatis di latar belakang sistem (background). Namun, dalam kasus yang dinilai darurat dan butuh penanganan segera, AI akan langsung melapor ke anggota community team Facebook.
Selain AI, Facebook meluncurkan juga beberapa tool penunjang, termasuk layanan chatting dengan organisasi-organisasi pencegahan bunuh diri via Messenger. Ada juga pengiriman informasi konsultasi secara langsung ke penyiar Facebook Live yang terindikasi bakal bunuh diri.
Sebelumnya, Zuckerberg pun sudah menulis “surat” di laman pribadinya di Facebook, tentang upaya mencegah berbagai bentuk penyimpangan pemakaian media sosial ini.
Tersirat, dia menitipkan pesan agar peran sosial dan komunitas tetap terbangun di sini, termasuk untuk mencegah tragedi, sekalipun infrastruktur teknologi sudah turun tangan.
Surat tertanggal 17 Februari 2017 itu pun tidak mengagungkan kecerdasan buatan sebagai solusi untuk efek samping media sosial. Alih-alih, Zuckerberg menggunakan judul “Building Global Community” untuk suratnya.
Setidaknya, bisakah kita tetap menjaga peduli di media sosial, bukan sekadar kepo, stalking, mem-bully, atau malah saling hujat?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.






























































