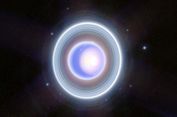KOMPAS.com - Saat masyarakat Aceh mulai melupakan tragedi gempa dan tsunami yang melanda persis 12 tahun silam, pada 7 Desember 2016, gempa M 6,5 mengguncang Pidie Jaya di pesisir timur provinsi ini. Gempa Pidie Jaya di zona belum terpetakan itu mengingatkan pentingnya membangun budaya siaga bencana.
Aceh yang kehilangan sekitar 170.000 warganya dalam gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 belum banyak belajar, terutama pentingnya bangunan tahan gempa.
Gempa yang melanda Pidie Jaya termasuk menengah, tetapi memicu kerusakan parah dan 104 korban tewas akibat tertimpa bangunan. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jumlah rumah rusak akibat gempa 8.582 unit. Sebanyak 2.874 unit rumah berada di Pidie Jaya, 63 rumah di Pidie, dan 149 rumah di Bireuen.
Bandingkan misalnya gempa dangkal berkekuatan M 7,8 yang melanda Selandia Baru, 13 November 2016, menewaskan dua orang. "Beberapa rekan peneliti dari luar negeri, khususnya Jepang, bertanya, mengapa gempa di Pidie Jaya yang relatif kecil menimbulkan banyak korban," sebut Rahma Hanifa, peneliti gempa bumi dari Institut Teknologi Bandung.
Survei oleh Badan Geologi menemukan, area terdampak gempa di Pidie Jaya memiliki struktur tanah rentan karena tersusun dari batuan lunak yang tebal. "Penguatan guncangan akibat gempa di Pidie Jaya mencapai enam kali," kata Sri Hidayati dari Badan Geologi.
Selain faktor kondisi tanah, menurut survei oleh peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Muzli, mutu bangunan buruk menjadi faktor utama banyaknya kerusakan. "Banyak bangunan rusak berat, tetapi bangunan di sampingnya utuh. Pengukuran memakai mikro tremor menunjukkan hal sama," ujarnya.
Kajian yang dilakukan tim Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menemukan banyak bangunan yang hancur dibangun setelah tahun 2004, termasuk bangunan pemerintah dan rumah sakit. "Banyak bangunan salah konstruksi. Misalnya, ditemukan kolom diisi pipa paralon serta banyak kesalahan sambungan antara kolom dan balok," kata Syamsidik, Wakil Ketua Tsunami dan Disaster Mitigation Research Center Unsyiah.
Situasi itu menunjukkan, gempa besar di Aceh 12 tahun silam belum memicu perubahan dalam prinsip membangun rumah aman gempa. "Kurang besar apa bencana 2004 sehingga tak menyadarkan untuk berubah. Cara warga membangun dan sikap pemerintah menerbitkan izin mendirikan bangunan tak berubah," ujarnya.
Manajemen bencana
Setelah gempa dan tsunami melanda Aceh, Minggu, 12 Desember 2004, kemajuan bidang manajemen penanganan bencana, khususnya gempa dan tsunami, di Indonesia berkembang pesat. Sistem peringatan dini tsunami atau Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) memungkinkan pemerintah mengirim peringatan tsunami lima menit setelah gempa.
Terakhir, sistem InaTEWS diuji saat gempa M 7,8 terjadi di Samudra Hindia, arah barat daya Kepulauan Mentawai, 2 Maret 2016, pukul 19.49 WIB. Pihak BMKG mengirim peringatan dini ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat pukul 19.56 WIB.
Meski gempa hanya memicu tsunami kecil dan tak ada kerusakan, hal itu membawa pelajaran penting. Kepanikan terjadi di masyarakat, khususnya di Kota Padang. Mayoritas warga mengungsi dengan kendaraan bermotor sehingga menimbulkan kemacetan. Respons pemerintah daerah pun tak seragam. Sebagian sirene tsunami dibunyikan, sebagian lain tak dinyalakan.
Kejadian itu mengulang peristiwa sama saat gempa M 8,5 mengguncang Samudra Hindia, 11 April 2012. Kepanikan melanda. Kemacetan terjadi di jalanan, dari Aceh, Padang, hingga Bengkulu. Hampir semua sirene tsunami tak dibunyikan atau terlambat berjam-jam. Alasannya, listrik padam atau petugas meninggalkan pos. Beruntung saat itu tak ada tsunami besar.
Sejauh ini, menurut Kepala BMKG Andi Eka Sakya, sistem InaTEWS mengalami banyak kemajuan. Tak beroperasinya lagi buoy tsunami yang dibangun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi karena biaya pemeliharaan mahal bisa ditutupi dengan pemodelan. "Masalah terbesar InaTEWS di hilir, yakni di masyarakat. Kita harus meningkatkan pemahaman dan respons warga, juga kesadaran menyiapkan diri menghadapi bencana," ucapnya.
Respons warga menjadi kunci penting. Apalagi, beberapa sumber tsunami amat dekat daratan, misalnya di Maluku atau Mentawai yang tsunaminya bisa datang kurang dari 10 menit, sehingga sistem peringatan dini tak lagi penting. Begitu gempa besar, warga harus segera mengungsi ke tempat tinggi. "Budaya sadar bencana jadi pekerjaan rumah," ujarnya.
Kesiapsiagaan menghadapi bencana pun belum membudaya di kalangan pemerintah. Itu terlihat dari sulitnya BMKG meminta peran daerah merawat sirene tsunami. Hingga 2016, BMKG membangun 52 sirene tsunami di Indonesia dan baru Pemerintah Provinsi Bali yang mengeluarkan dana perawatan. Di daerah lain, termasuk Aceh, biaya perawatan ditanggung pemerintah pusat.
Untuk kesiapan operasional, sirene tsunami biasanya dibunyikan setiap tanggal 26. Namun, di Aceh belum dibunyikan dengan keras karena dikhawatirkan memicu kepanikan warga (Kompas, 6/10/2016).
Pendidikan kesiapsiagaan bencana di Aceh dan daerah lain menjadi pekerjaan rumah. Latihan evakuasi gempa dan tsunami beberapa kali dilakukan di sekolah, tetapi menurut riset Sakurai (2016), hal itu tergantung pihak luar. Selama budaya sadar bencana belum terbentuk, kesiagaan tak jadi arus utama. Jadi, bencana akan kembali dilupakan dan korban berjatuhan....
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.