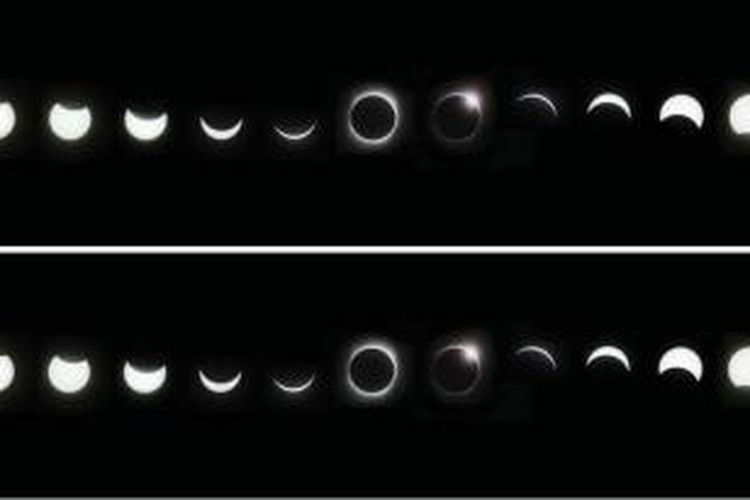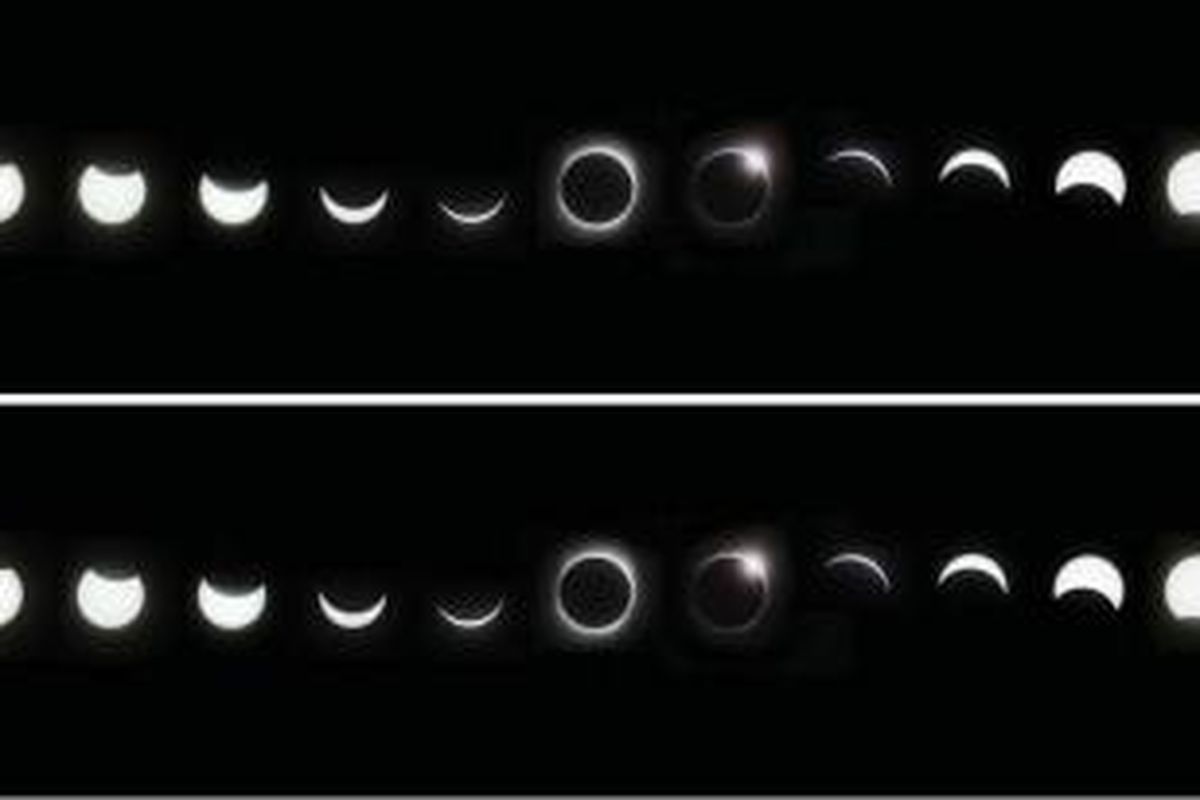
KOMPAS.com — Dikisahkan, pada suatu ketika, para dewa berhasil menemukan tirta amerta setelah mencarinya ke lautan susu. Tirta amerta begitu penting karena dengan meminum air itu, seseorang akan hidup abadi.
Para dewa yang bersukacita kemudian berkumpul di kahyangan dan berbaris untuk meneguk tirta amerta. Namun, di antara mereka ada raksasa bernama Kala Rahu yang menyamar sebagai dewa demi mendapatkan keabadian.
Tepat saat dia mendapat giliran untuk minum air abadi, penyamarannya diketahui Dewa Surya dan Dewa Candra.
Kedua dewa yang mewakili matahari dan bulan itu kemudian berteriak. Dewa Wisnu, yang membagikan air itu, segera menarik cawan dari mulut Kala Rahu dan mencabut senjata cakra. Roda cakra berputar, dan menebas leher Kala Rahu.
Namun, raksasa Rahu telah meminum sedikit tirta amerta. Air abadi itu mengalir hingga tenggorokannya. Akibatnya, kepala Rahu tetap hidup, sedangkan badannya mati. Rahu kemudian melayang-layang tanpa badan sepanjang hayatnya.
Rahu menyimpan dendam kepada Dewa Surya dan Dewa Candra. Oleh karenanya, raksasa itu bersumpah, ia selamanya akan mengejar dan menelan kedua dewa itu. Kadang-kadang, Kala Rahu berhasil mencaplok Surya dan Candra. Saat itulah, gerhana matahari atau gerhana bulan terjadi.
Dalam kebudayaan Jawa, Bali, dan budaya lain yang dipengaruhi Hindu, Kala Rahu dikenal sebagai Batara Kala. Setiap kali ia berhasil menelan matahari, orang-orang segera memukul lesung, kentongan, dan membuat suara-suara nyaring agar Kala pergi dan memuntahkan matahari.
Cerita Batara Kala menelan matahari itu tercatat di Candi Belahan di Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Kompas edisi 7 Maret 2016, di halaman 16 dengan judul "10 Abad Jejak Gerhana di Nusantara", menuliskan, relief di candi peninggalan Kerajaan Mataram tersebut menggambarkan sosok raksasa Batara Kala hendak menelan medalion atau bulatan.
Di bawah bulatan itu, ada dua sosok yang ditafsirkan sebagai Dewa Surya atau Dewa Matahari dan Dewi Candra atau Dewi Bulan. Bulatan itu diduga sebagai matahari atau bulan.
Cerita serupa dengan alur berbeda dengan Rahu sebagai tokohnya juga beredar di masyarakat Bangka. Rau, begitu dia disebut, adalah raksasa yang ingin mempersunting dewi dari kahyangan. Cintanya ditolak, amarahnya memuncak. (Baca: Gerhana dan Dendam Abadi Raksasa Rau)
***
Mitos soal gerhana ketika matahari hilang ditelan makhluk lain bukan hanya ditemukan di kebudayaan yang dipengaruhi Hindu.
Dalam keyakinan kuno Tiongkok, gerhana diyakini sebagai peristiwa ketika seekor naga raksasa menelan matahari. Cerita naga ini serupa dengan legenda masyarakat Ternate yang menganggap gerhana terjadi karena ada naga menelan sang surya.
Dalam artikel Kompas pada 10 Februari 2016, mitos naga menelan matahari Tiongkok ini ternyata tercatat sejak sekitar 4.000 tahun silam. Pada 22 Oktober tahun 2134 sebelum Masehi, gerhana matahari total terjadi di daratan Tiongkok.
Akibat peristiwa tersebut, berkembanglah mitos adanya naga murka dan berupaya melahap matahari. Masyarakat membunyikan suara-suara keras seperti petasan.
Para prajurit Tiongkok kuno dikerahkan untuk menembakkan meriam ke arah matahari pada saat gerhana matahari berlangsung. Tindakan itu dilakukan agar matahari kembali bersinar.
Menurut Henky Honggoh, pemerhati budaya Tionghoa di Palembang, Jumat (5/2/2016), naga merupakan simbol suci bagi masyarakat Tionghoa. Naga memiliki makna kehidupan dan keberuntungan bagi masyarakat Tionghoa. Beragam simbol naga ada di segala aspek kehidupan masyarakat Tionghoa.
"Di dalam mitos naga memakan matahari itu terkandung makna yang buruk karena sinar matahari menghilang yang diartikan menjadi sebuah bencana. Namun, membunyikan petasan dan bebunyian lainnya menjadikan simbol kekuatan lain dari manusia yang mampu mengusir kekuatan yang jahat itu," ujarnya.
Sementara itu, di Skandinavia, masyarakat di Denmark, Swedia, dan Norwegia meyakini bahwa makhluk penelan matahari adalah serigala bernama Skoll. Sedikit berbeda, di Korea, makhluk yang mengejar-ngejar surya adalah anjing, sedangkan di Vietnam adalah kodok.
Hampir semua kebudayaan di dunia memiliki kisah soal gerhana. Kisah-kisah itu muncul karena manusia selalu mencari jawaban atas fenomena yang tidak diketahuinya.
Manusia berusaha memahami gerhana sesuai dengan kemampuan pikir dan zamannya. Usaha manusia memahami semesta dan dinamikanya itu melahirkan mitos.
"Mitos berkembang atau dikembangkan untuk menjawab pertanyaan mendasar manusia tentang diri dan lingkungannya," kata ahli mitologi Universitas Indonesia, Dwi Woro Retno Mastuti, Kamis (28/1/2016). "Mitos terlahir salah satunya sebagai usaha manusia memahami peristiwa semesta."
(Baca: Mitos Penambah Daya Pikat Gerhana)
Kisah kuno raksasa dan naga menelan matahari yang kini terkesan jauh dari rasionalitas itu dibingkai sesuai zaman untuk memahami keadaan semesta yang sangat jauh dari jangkauan kemampuan pikiran manusia saat itu.
Namun, dalam perkembangannya, manusia kemudian menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan dan mendapati jawaban-jawaban yang semakin rasional.
Sebelum Masehi, ilmuwan Babilonia bahkan sudah bisa meramalkan terjadinya gerhana dengan mengamati gerakan bulan dan matahari.
Kini, gerhana adalah peristiwa alam yang bisa dijelaskan dengan gamblang oleh ilmu pengetahuan. Peneliti sudah dapat meramalkan terjadinya gerhana dan durasinya, hingga hitungan detik. Ilmuwan bahkan memanfaatkan gerhana untuk membuktikan teori-teori lain di alam semesta.
Lalu, apakah cerita soal raksasa dan naga menjadi tidak relevan? Jawabannya tentu tergantung pandangan tiap-tiap orang dan dari sudut mana jawaban akan ditarik.
Secara budaya, cerita naga dan raksasa kini hadir dalam bentuk seni dan festival. Beragam pesta di seputaran momentum gerhana pun digelar di beberapa daerah.
Di Palembang, Sumatera Selatan, misalnya, gerhana bakal disambut dengan tari-tarian dan melibatkan lampion naga sepanjang 18 meter.
Sebanyak 20 siswa SMKN 7 Palembang membuat lampion naga sebagai bagian dari tarian kolosal Naga Memakan Matahari saat puncak gerhana matahari total.
Masyarakat dayak di Kalimantan Tengah menyambut gerhana dengan menabuh aneka alat musik. Saat kegelapan total terjadi, 55 kentongan atau disebut salakatok akan ditabuh agar kegelapan berakhir, dan hal negatif dijauhkan.
Selain itu, masih banyak kegiatan budaya lain terkait gerhana yang disajikan berdasarkan mitos dan cerita rakyat. Artinya, secara budaya, mitos itu masih relevan.
Mengenai hal itu, budayawan Sujiwo Tejo dalam akun Twitter-nya, @sudjiwotedjo, menuliskan, "Fenomena geometris gerhana matahari diterima, tetapi lakon matahari dimakan Batara Kala tetap diperlukan sebagai bumbu."
Rupanya, pada era modern, kisah dan simbol itu masih memiliki daya pikat untuk menjadi sumber inspirasi dan kreasi hiburan terkini. Mitos tidak akan lekang oleh waktu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.