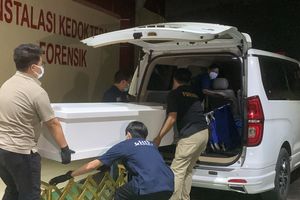Durban dan Peta Jalan Bali
Pertemuan para pihak (COP) itu lengkapnya terkait dalam Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim PBB (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC). Di antaranya ada Tim Transisi yang ditugaskan Pertemuan Cancun untuk merancang operasionalisasi Dana Iklim Hijau (the Green Climate Fund), yang akan melaporkan hasil kerja.
Negara-negara Afrika akan mendorong agar Komite Adaptasi segera beroperasi menjalankan tugas. Bencana alam sebagai akibat dari perubahan iklim telah melanda Afrika, Asia, dan belahan bumi lainnya sehingga gerakan kolektif mengatasi masalah adaptasi sangat diperlukan. Negara-negara berkembang juga mendambakan lahirnya Pusat Teknologi Perubahan Iklim dan jaringannya seperti telah disepakati bersama.
Akses pada teknologi adaptasi dan mitigasi berikut mengenai hak akan kekayaan intelektualnya menjadi penting bagi negara berkembang dalam pelaksanaan UNFCCC. Sejumlah masalah peka seperti langkah-langkah perdagangan unilateral dan akses yang sama pada pembangunan berkelanjutan juga dibahas.
Isu yang menarik adalah bagaimana Durban memutuskan kelanjutan dari komitmen negara maju (Annex 1) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) secara signifikan seperti tertuang dalam Protokol Kyoto. Panel Internasional Perubahan Iklim (IPCC) telah menyampaikan laporan bahwa jika gaya hidup manusia tidak berubah dan emisi dunia tidak ditekan signifikan, panas bumi akan bertambah dua derajat celsius tahun 2050. Ini akan menimbulkan bencana dahsyat, seperti mencairnya gletser dan meningkatnya permukaan air laut.
Mengingat komitmen negara-negara maju yang termasuk Annex 1 jatuh tempo tahun 2012, masyarakat menunggu kesepakatan baru di Durban dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca.
Peta Jalan Bali memiliki dua komponen berbeda. Pertama adalah disepakatinya Rencana Aksi Bali (Bali Action Plan) yang meluncurkan proses negosiasi di bawah UNFCCC. Ini untuk mencapai kerja sama jangka panjang dalam rangka melaksanakan kesepakatan secara efektif, utuh, dan berkelanjutan.
Dalam proses ini AS yang bukan merupakan negara pihak Protokol Kyoto ikut serta dalam negosiasi. Kedua, mandat hukum yang terpisah untuk meluncurkan negosiasi di bawah Protokol Kyoto guna mencapai kesepakatan komitmen kedua dari negara-negara maju untuk mengurangi emisi GRK jika komitmen pertama Protokol Kyoto jatuh tempo 2012.
Perundingan dalam kerangka Protokol Kyoto seharusnya sudah tuntas pada 2009 sehingga cukup waktu untuk proses hukum selanjutnya seperti ratifikasi. Akan tetapi, negara maju menentang memberikan komitmen kedua karena dianggap sebagai komitmen unconditional.
Menurut kelompok negara maju, negara berkembang seperti China, India, Brasil, dan Afrika Selatan juga termasuk major emitters (penghasil emisi karbon utama). Maka negara maju menginginkan beban pengurangan emisi gas rumah kaca tak hanya dipikul negara dalam Annex 1, tetapi juga oleh pencemar besar lain. Malah Jepang dan Australia mengusulkan segera diluncurkan perundingan untuk merumuskan instrumen baru yang mengikat secara hukum (legally binding instrument). Dengan demikian, ada rezim hukum baru yang juga mengikat China, India, Brasil, dan Afrika Selatan selain negara Annex 1.
Kelompok 77 yang merupakan kelompok perunding negara berkembang bereaksi keras terhadap posisi negara maju. Empat hal dikemukakan sebagai dasar argumentasi.
Pertama, kesanggupan negara maju untuk mengurangi emisi GRK ternyata jauh di bawah target, tidak sesuai dengan kajian iptek dan dengan level tanggung jawab sebagai pencemar besar pendahulu.
Kedua, ada upaya menggoyahkan sistem dari kesepakatan terdahulu yang merupakan hasil perundingan lama. Seakan suatu proses negosiasi baru dalam mengubah aturan main yang ada.
Ketiga, tidak menghormati prinsip yang telah disepakati mengenai Prinsip Tanggung Jawab Bersama tapi Beda (equity and common but differentiated responsibility).
Keempat, negara-negara maju dianggap sering memberikan janji kosong untuk membantu negara berkembang mengenai keuangan, teknologi, serta pengembangan kapasitas dan adaptasi. Di Kopenhagen, beberapa negara maju berjanji memberikan dana segar sekitar 30 miliar dollar AS untuk periode 2009-2012. Janji yang lain adalah memberikan dana tambahan 100 miliar dollar AS setiap tahun setelah 2020. Ternyata, jumlahnya tidak seperti harapan dan kebanyakan adalah dana dari komitmen lama.
China dan India berargumen bahwa di negara mereka perbandingan emisi GRK dengan jumlah penduduknya sangat rendah dibandingkan dengan negara maju. Maka mereka menganggap tidak adil jika negara berkembang mendapat beban yang sama. Karena tanggung jawab historis, negara-negara maju juga memiliki emisi per kapita tinggi dibandingkan dengan emisi per kapita negara berkembang.
Menghadapi perbedaan sikap ini, pandangan masyarakat internasional berpaling ke Indonesia. Mereka menganggap Indonesia mewakili kedua belah argumen yang berseteru. Pertama, Indonesia adalah negara kepulauan sehingga sangat peka terhadap perubahan permukaan air laut. Kedua, Indonesia adalah negara berkembang yang berpacu membangun negeri.
Dalam konteks ini, Indonesia mengikuti pandangan Ki Hadjar Dewantoro yang menganjurkan ”Ing Ngarso Sung Tulodo”. Di tengah tiadanya kesepakatan global, Indonesia bersedia secara sukarela mengurangi emisi GRK sebesar 26 persen atas kekuatan sendiri dan 41 persen dengan bantuan asing. Namun, inisiatif ini belum memecahkan kebuntuan perundingan. Akibatnya, Indonesia hanya memberikan prioritas pada aspek spesifik yang memiliki dampak langsung nasional.
Sebagai negara kepulauan terbesar, negara berpenduduk terbesar keempat, negara demokrasi terbesar ketiga, dan sebagai anggota G-20, Indonesia sebaiknya jangan terfokus pada masalah Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation dan komitmen bilateral dengan Norwegia saja. Indonesia perlu ikut aktif mendorong agar Peta Jalan Bali menjadi kenyataan.
Indonesia perlu berusaha agar kemajuan tidak hanya terjadi di Kelompok Kerja Ad Hoc (AWG) terhadap Kesepakatan Komitmen Jangka Panjang, tetapi juga di AWG Protokol Kyoto. Masalah perubahan iklim tak dapat ditangani sendiri, tetapi sebaiknya dilakukan kolektif.