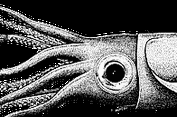Biarkan Warga Menjaga
Skema Juma— yang pertama kali bergulir tahun 2008—ini praktis menjadi model strategi global untuk mempertahankan keutuhan hutan dengan mengurangi emisi karbon. Inilah bentuk jual-beli antara masyarakat negara maju dan negara berkembang. Rakyat di Juma dibayar perusahaan swasta dari negara-negara kaya untuk tidak membabat hutan.
Salah satu yang terlibat dalam skema yang disebut Programa Bolsa Floresta itu adalah jaringan hotel ternama Marriott. Selain mendonasikan 2 juta dollar AS, mereka juga mengutip 1 dollar AS per malam dari tamunya untuk penduduk yang tinggal di hutan itu. Kalkulasinya, dana yang ditebar ”pembeli”—hotel, perbankan, dan pasar swalayan—ke proyek Juma hingga tahun 2050 bisa mencegah pembalakan hutan sampai 62 persen. Ini bisa menghemat pelepasan karbon sampai 210.000 ton.
Bisakah skema ini menjamin keadilan dan membawa manfaat, terutama bagi masyarakat yang menghuni hutan itu, yang secara turun-temurun hidup dari manfaat hutan? Jawabannya berpulang kembali kepada para pihak, terutama pemerintah setempat dan lembaga pembeli karbon. Sejauh mana niat mereka terlibat dalam upaya global mengurangi emisi karbon?
Bagi Rudolf Boriam, warga Kampung Wembi, Kabupaten Keerom, Papua, niat baik pemerintah tak tampak. Puluhan tahun lalu, terutama awal tahun 1980-an, banyak hutan adat di kawasan itu diambil alih oleh pemerintah dan berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Walhasil, 45.000 hektar hutan di kampungnya kini telah berpindah kepemilikan.
Pada April lalu, dinas kehutanan provinsi datang lagi. Kali ini mereka hendak mengukur hutan adat warga yang berada di timur kampung, persis di pinggir perbatasan dengan Papua Niugini seluas 36.000 hektar. Kabarnya, hutan itu hendak dijadikan sebagai hutan lindung.
”Kali ini kami tidak mengizinkan. Kalau mau jadi hutan lindung, biar kami sendiri yang melindunginya. Apalagi di hutan itu ada tempat keramat, yang kami percayai sebagai tempat di mana suku kami, suku Manem, bermula,” kata Rudolf.
Dari kacamata budaya, penolakan warga Wembi dapat dipahami. Bagi mereka, hutan tidak hanya menjadi sumber hidup, tetapi juga bagian integral dalam sejarah keberadaan mereka. ”Tiap wilayah telah dibagi oleh nenek moyang kami kepada masing-masing marga. Hutan yang dibagi-bagi itu menjadi jaminan hidup bagi masing-masing marga,” kata Rudolf.
Dari hutan itu mereka mendapat buah-buahan, rotan, dan kayu. Mereka percaya, ketika hutan itu dilepaskan, lepas pula ikatan itu dan mereka akan menerima hukuman. Fakta bahwa beberapa kelompok masyarakat asli di Keerom jatuh miskin—setelah hutan yang mereka miliki dilepaskan kepada pemerintah untuk dijadikan kebun kelapa sawit—menjadi bukti dari terpenggalnya relasi itu.
Tak heran, soal REDD+, mereka pun menanggapinya dingin. ”Biar kami sendiri yang menjaga hutan kami,” kata Rudolf.
Apa yang dikhawatirkan Rudolf sangat bisa dipahami oleh Direktur Program WWF Papua Benja Mambai. Karena itu, pihaknya ingin program REDD+ digulirkan berbasis pada prinsip berkelanjutan. Yang tak kalah penting adalah sikap tidak memaksakan kehendak dan menghormati apa pun keputusan masyarakat adat.
Saat ini di Papua, WWF sedang membangun kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk program REDD+, meliputi kawasan hutan seluas 450.000 hektar yang tersebar di Kecamatan Urunum Guay, Yapsi, dan Kaure di Kabupaten Jayapura.
Dengan bantuan dari ahli pemetaan geografi dari Universitas Gadjah Mada dan ahli antropologi dari Universitas Indonesia, WWF Papua menyimpulkan hutan di wilayah itu memiliki potensi karbon yang cukup.
”Kami menyimulasikan, jika per ton per hektar karbon dihargai sebesar 4 dollar AS, dengan asumsi 25 persen digunakan sebagai asuransi, maka setiap tahun masyarakat akan menerima hasil sebesar Rp 12 miliar. Itu baru hitungan di atas kertas,” kata Benja.
”Untuk REDD, yang terutama adalah penguatan masyarakat, terutama dalam mengelola dana yang diperoleh. Lebih dari itu, jika dalam proyek itu diadakan kontrak, rakyat sebaiknya tidak melepaskan hak kepemilikan atas lahan itu,” kata Lindon Pangkali dari Foker LSM Papua.
Melibatkan masyarakat setempat memang merupakan isu utama pelaksanaan REDD+. Oleh karena itu, Teras Narang, Gubernur Kalimantan Tengah—
Jika berhasil menjaga hutan di sekitarnya, warga akan memberikan kompensasi, selain menyediakan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Selain itu, kata Teras, mereka tidak dilarang masuk dan mengakses hutan yang ada, termasuk untuk keperluan bertani dan memelihara ikan.
Akan tetapi, menurut Arie Rompas, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng, kompensasi bagi warga sekitar hutan masih belum jelas. Mereka hanya mendengar bahwa bentuk kompensasinya adalah uang tunai.
Yang mengkhawatirkan sebetulnya justru keterlibatan pihak swasta dengan kepentingan warga. ”Jangan sampai keberadaan program ini justru menutup akses masyarakat yang terbiasa memanfaatkan sumber daya di sekitarnya. Jangan sampai masyarakat terpinggirkan,” kata Arie.
Bagi Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan, sebetulnya mudah melaksanakan REDD+. Caranya adalah menjadikan masyarakat adat sebagai penyelenggara, mengingat hutan alam—termasuk lahan gambut—di Republik ini sebagian besar merupakan wilayah adat.
”Jadi, tinggal pemerintah melindungi dan mengakui masyarakat adat, serta menyerahkan kepada mereka untuk merawat hutan. Dengan pengetahuan tradisional dan ajaran leluhur yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun, masyarakat adat pasti bisa menjaganya. Itulah yang mereka lakukan selama ini sebelum hutan diserahkan pemerintah kepada pengusaha kelapa sawit dan perusak hutan,” tegas Abdon. ”Masyarakat adat harus dilihat sebagai solusi, bukan sumber masalah.”