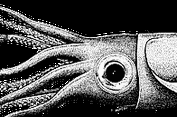Nenek Moyang Kaum Indo
ACHMAD SUNJAYADI
Sebutan nyai pada masa kolonial ditujukan kepada perempuan muda, setengah baya yang menjadi ”gundik” atau ”perempuan simpanan” orang asing, khususnya orang Eropa. Sebutan ini, menurut anggapan orang Eropa pada masa itu, setara dengan concubine, bijwijf, atau selir yang meniru kebiasaan para raja di Nusantara.
Reggie Baay, yang sebelumnya menulis roman De Ogen van Solo (2006), dalam buku ini menelusuri akar per-nyai-an dengan menggunakan titik awal sejarah keluarganya. Baay yang ternyata cucu dari seorang nyai (Moeinah) tidak hanya menelusuri akar keluarganya, tetapi juga mewawancarai anak- anak dan cucu-cucu dari para nyai yang lain serta mengumpulkan foto-foto mereka.
Seperti kata pepatah: sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Baay tidak hanya mendapatkan informasi tentang asal-usulnya, ia juga mendapat informasi bagaimana nasib beberapa nyai tersebut sekaligus meramunya dengan sumber-sumber sejarah serta karya sastra sezaman dan modern.
Deretan karya sastra dan catatan perjalanan yang digunakan membentang dari akhir abad ke-19 hingga abad ke-20, seperti Justus van Maurik, PA Daum, Victor Ido, Augusta de Wit, G Francis, Louis Couperus, Dé-Lilah, Johan Fabricius, Otto Knaap, E Du Perron, Annie Foore, H Gorter, Thérèse Hoven, J Kleian, Herman Kommer, MC Kooy-van Zeggelen, Mina Kruseman, L Székely, MH Székely-Lulofs, Bas Veth, Marie van Zeggelen, Ferdinand Wiggers, Willem Walraven, Lin Scholte. Baay juga menggunakan terjemahan karya Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa, sebagai sumber.
Baay membagi bukunya dalam beberapa bagian. Ia membahas akar concubinat atau pergundikan sampai abad ke-19 yang merupakan konfrontasi antarras. Selanjutnya, ia mengurai hubungan antara tuan dan pelayan pribumi, pergundikan dalam dunia sipil, militer (dalam tangsi), dan perkebunan-perkebunan di Deli. Tidak ketinggalan, anak-anak Indo Eropa sebagai hasil hubungan antara tuan (baca: Eropa) dengan pelayan pribumi, hingga akhir dari pergundikan di Hindia Belanda juga dijabarkan. Baay juga meramu akibat hubungan antara para nyai dan tuannya secara psikologis, ekonomi, sosial, dan budaya.
Membicarakan nyai berarti menelusuri sejarah terbentuknya status dan institusi ini dalam masyarakat kolonial di Hindia Belanda, khususnya pergeseran makna nyai dalam masyarakat. Dalam Encylopaedie Nederlandsch Indië (1919), nyahi (nyai) merupakan panggilan kehormatan untuk perempuan yang lebih tua.
Istilah nyai dipasangkan dengan kiai, gelar kehormatan bagi seorang pria yang dianggap lebih tua serta mumpuni dalam ilmu dan pengalaman hidup. Dengan demikian, istilah nyai mengalami pergeseran seiring dengan berdatangannya perempuan kulit putih (Eropa) ke Hindia. Menurut Jean Gelman Taylor, pergeseran istilah nyai sebagai ”pembantu pribumi” bagi pria Eropa berlaku sejak awal 1826 meskipun sebenarnya jauh sebelumnya istilah nyai sudah dipakai.
Seperti yang ditulis oleh Rijckloff van Goens, utusan VOC dalam laporannya ketika melakukan perjalanan ke Mataram tahun 1666, ia menyebutkan bahwa ada sekelompok perempuan setengah baya yang bertanggung jawab menjaga keamanan istana serta urusan raja dengan para selirnya di luar istana: ”Over alle dese waren mijn jonghste aenwesen 2 vrouwen tot opperste hoofden, de eene genaemt Injey Maes, ende d’andere Injey ’t Chela” (Mengenai semua ini, ada dua nyai yang ditunjuk memimpin mereka, yaitu Injey—Nyai Maes dan yang lain Injey—Nyai Chela). Sebagai tambahan keterangan untuk Injey atau Nyai ini disebutkan: ”Injey/Njai is eerbiedwaardigheidstitel voor een oudere vrouw van aanzien” (Nyai adalah gelar kehormatan untuk seorang perempuan yang dianggap lebih tua).
Di antara berbagai tulisan yang membahas kisah per-nyai-an atau yang lebih sering disebut sebagai concubinat (pergundikan) di Hindia Belanda, dalam buku ini diungkapkan pula nasib beberapa nyai, mulai dari nyai pribumi, Tionghoa, hingga Jepang.
Misalnya kisah Lamira kelahiran Surabaya tahun 1853. Ia beribu seorang Jawa dan ayahnya dari kalangan Mardijker, para peranakan Portugis yang masih bisa berbicara bahasa Portugis. Lamira bertemu dengan Johannes, seorang Indo-Eropa yang bekerja sebagai juru sita di Kediri, Jawa Timur. Johannes lalu menjadikan Lamira sebagai nyai dan hidup layaknya suami-istri.
Mereka dikaruniai empat anak. Pada tahun 1881 Johannes meninggal dunia. Anak-anak mereka diadopsi oleh keluarga Johannes sehingga mendapat hak seperti orang Eropa. Lamira kemudian menikah dengan seorang Eropa dan akhirnya pergi ke Belanda. Ia tutup usia pada usia 105 tahun di Den Haag.
Kisah nyai yang lain adalah kisah Saila yang lahir dari sebuah keluarga miskin di Jawa Barat tahun 1884. Saila tidak bisa membaca. Ia hanya dapat bicara bahasa Melayu dan paham bahasa Belanda. Ia bertemu dengan Edward dari Belgia. Tahun 1900, ia dijadikan nyai oleh Edward. Dari Edward, Saila mendapatkan delapan anak: lima perempuan dan tiga laki-laki.
Edward yang bekerja sebagai sipir penjara mendapat nasib sial. Ia tewas ketika bekerja. Anak-anak yang masih kecil dititipkan di panti asuhan Vincentius, Batavia. Sementara anak-anaknya yang lebih tua telah menikah. Saila pun akhirnya menikah dengan seorang pribumi dan dikaruniai seorang anak. Namun, Saila masih tetap berhubungan dengan anak-anaknya dari Edward. Anak-anak yang paling tua pun membantu secara finansial, di samping mendapat uang pensiun dari Edward.
Ketika pecah perang, anak-anak Saila tidak dimasukkan ke dalam kamp karena mereka berdarah campuran. Seusai perang, anak-anak Saila berangkat ke Belanda. Saila tetap tinggal di Indonesia. Ia tinggal dengan anak laki-lakinya yang paling kecil di sebuah rumah kecil di Jakarta. Saila meninggal tahun 1972 di usia 88 tahun. Sebagai kenangan atas Saila, seorang cicitnya diberi nama Saila.
Kisah di atas adalah sebagian dari nasib para nyai di Hindia Belanda. Mungkin ada juga nyai yang nasibnya jauh dari beruntung. Tak diingat, tak dikenang, dilupakan begitu saja. Dihilangkan sebagai sumber asal-usul suatu generasi. Namun, kenyataannya, peran mereka tidak dapat dihilangkan, yaitu perannya membentuk salah satu budaya di Indonesia, budaya Indo (Indis). Buku ini tidak hanya mengungkap sisi kelam kolonialisme, tetapi juga memperlihatkan jejak satu ”institusi” yang sebenarnya dilembagakan sejak adanya kebijakan VOC pada tahun 1652. Jejak sejarah yang memberikan warna pada negeri ini.