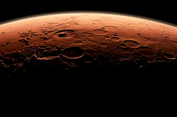Siang Hari Pun Nyanyian Kodok itu Terdengar
ADONARA - Minggu, 10 Agustus 2008. Pada pukul 08.00 Wita, dibantu seorang warga Desa Demondei, Fritz Samon (10), saya berjalan kaki menempuh perjalanan 12 kilometer dari Desa Mewet di pesisir pantai menuju Demondei di atas ketinggian 1.009 meter dari permukaan laut. Demondei adalah salah satu desa terpencil di pedalaman Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.
Kami melintasi lima sungai. Air sungai itu sangat jernih dan dingin. Siang hari masih terdengar bunyi katak yang saling bersahutan di sekitar sungai. Sementara burung beterbangan sambil bernyanyi dari ranting yang satu ke ranting lain. Suasana ini benar-benar terasa asri.
Jalan setapak sepanjang 12 kilometer itu berkelok-kelok, terus menukik sepanjang punggung dan pinggang bukit-bukit kecil, lalu menuruni jurang terjal, melintasi sungai, dan melewati lembah.
Warga setempat menempuh jalan itu hanya dua jam sambil membawa beban 10-70 kg di kepala atau pundak. Jalannya begitu cepat meski mendaki. Jalan seperti itu sudah bertahun-tahun mereka lakukan. Warga dari luar desa, seperti Kupang, harus butuh 4,5 jam perjalanan.
Kelelahan begitu mengganggu perjalanan. Bagian betis dan pergelangan kaki seakan mau terlepas. Napas terengah-engah. Setiap lima langkah harus berhenti menarik napas dan mengumpulkan tenaga baru.
Akan tetapi, Fritz, bocah warga Demondei yang menjemput di pertigaan Mewet, berjalan dengan santai sambil bernyanyi. Padahal, ia membawa tas pakaian dan 5 kg beras sebagai bekal.
Sekitar 1,5 km menuju desa, perjalanan benar-benar menukik. Leher terus memanjang dengan kepala tegak memandang ke atas menyusuri punggung Gunung Ile Pati. Konon, pada waktu silam ada seorang warga pelarian dari Maluku bernama Pati menetap di gunung ini. Itulah kisahnya sehingga gunung tersebut bernama Ile Pati, artinya Gunung Pati. Pati kemudian menurunkan suku Bubun, salah satu suku yang mendiami Desa Demondei.
Di sisi kiri-kanan ruas jalan itu terdapat tumpukan kayu olahan milik pengusaha dari Waiwerang dan Larantuka. Kayu-kayu berkualitas sedang itu dirambah di Gunung Ile Pati untuk dijual ke Kupang atau Larantuka.
Pukul 12.30 Wita kami tiba di Demondei untuk mengikuti upacara adat Tuno Manuk, memanggil dan melindungi para perantau dari desa itu. Tampak di desa itu sudah ada beberapa wajah baru. Mereka adalah warga Demondei yang berdomisili di Kupang atau kota lain.
Setiap ada tamu baru, bocah-bocah di desa itu berdatangan. Mereka berdiri memadati pintu masuk rumah dan sebagian mengelilingi rumah sambil mengintip. Ketika disodori gula-gula, mereka saling berebutan.
Demondei terletak persis di tengah Pulau Adonara, batas akhir pandangan mata dari arah selatan atau arah utara garis pantai. Cuaca begitu dingin meski matahari tampak cerah. Jaket tebal yang saya kenakan tidak mampu mengusir rasa dingin. Sebaliknya, orang-orang desa tidak merasa terganggu dengan cuaca itu.
Sekitar 320 rumah bambu dengan atap seng berdiri kokoh di desa ini. Dari puncak pulau itu, tepatnya antara Desa Demondei dan Watodei, terlihat bentangan air laut di wilayah selatan, dekat Pulau Solor dan wilayah utara, Laut Flores.
Di tempat yang disebut punggung Gunung Ile Pati itu telepon seluler mendapat sinyal, tetapi hanya satu strip. Saya sempat membaca lima SMS yang masuk setelah dua hari tidak pernah mendapat sinyal atau di luar jangkauan.
Jika ingin menelepon dengan suara yang kedengaran jelas, kami harus berjalan kaki menuju puncak Ile Pati sekitar 500 meter lagi. Perjalanan itu harus melewati hutan yang penuh lintah.
Pukul 16.00 Wita terlihat warga desa bergegas menuju sebuah mata air, sekitar 100 meter dari desa itu. Di sana mereka mandi dan mengambil air bersih langsung dari sumber.
Perkebunan kopi, cokelat, pinang, kelapa, vanili, dan cengkeh tampak memadati sumber air itu sampai jauh. Tidak ada lagi perdu, hutan savana atau rumput liar seperti di daratan Pulau Timor atau Sumba..
Meski cuaca dingin sampai 18 derajat Celsius, warga setempat mandi seperti biasa. Ada dua mata air berdekatan sekitar 50 meter, masing-masing untuk perempuan dan laki-laki.
Demondei adalah salah satu dari puluhan desa yang masih terisolasi di Pulau Adonara. Dari kondisi wilayahnya, pulau itu terkesan jarang mendapat perhatian pemerintah. Angka buta huruf di Demondei mencapai 1.210 orang, 620 di antaranya anak usia sekolah. Juga dari 3.200 jiwa penduduk desa itu, sekitar 1.200 orang ada di Malaysia sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI). Setiap 2-3 tahun mereka pulang untuk membangun rumah dan melunasi mas kawin.
Pendidikan pun tertinggal. Hingga kini hanya satu orang dari Demondei yang berpendidikan strata satu (S-1) dan dua orang lulusan diploma.
Malam hari desa itu tampak gelap gulita. Tidak ada listrik dari PLN. Para perantau dari desa itu pada tahun 2005 menyumbang satu mesin genset dengan kemampuan menerangi 150 rumah. Akan tetapi, warga kampung kesulitan mendapat solar sehingga mesin genset itu enam bulan terakhir tidak digunakan. Solar harus dibeli di Waiwerang, sekitar 25 km, sejauh 12 km di antaranya harus ditempuh dengan berjalan kaki.
Kini warga menggunakan lampu pelita. Namun, karena minyak tanah jauh dari pasar, sebagian besar warga menggunakan daging buah kemiri yang ditumbuk halus bersama kapas, kemudian dibalutkan pada batangan lidi, lalu dibakar hingga menyala untuk penerangan di rumah.
Tidak ada kios di desa itu, kecuali beberapa warga yang menjual rokok dan arak. Dua barang ini laris di desa itu. Malam menjelang tidur kebanyakan kaum pria menenggak arak dan merokok terlebih dahulu agar tidur lebih lelap, tidak terpengaruh rasa dingin.
Sebagian besar rumah beratap seng dan berdinding bambu. Malam hari cuaca sangat dingin sampai atap seng mengeluarkan embun dan menetesi penghuni rumah. Kebanyakan rumah tanpa plafon.
Pendatang baru di desa itu tidak dapat menghindari sakit radang tenggorokan, flu, batuk, dan pilek. Di desa itu tidak ada bidan desa atau polindes. Jika sakit, warga harus berjalan kaki 15 km menuju puskesmas di Baniona.
Lolongan anjing di tengah kegelapan mengusik rasa sepi di tengah malam. Suasana begitu gelap, hanya terdengar suara gong dan tambur sebagai tanda memulai upacara adat di desa itu.
Tidak ada televisi, radio, atau deringan telepon seluler. Telepon genggam pun cepat kehabisan baterai karena dingin. Namun, di tengah kegelapan itu, penghuni rumah terus bekerja menguliti buah pinang untuk dikeringkan.
Tidak ada WC di sekitar rumah. Pagi hari para tamu atau pengunjung bersama penduduk setempat pergi ke hutan sekitar guna membuang hajat atau air kecil. Anjing, ayam, dan ternak babi berkeliaran di sekitar hutan itu.
Meski sanitasi buruk, kebanyakan warga tampak sehat. Mereka tidak tertular penyakit diare atau muntaber, kecuali penyakit kulit, seperti panu dan kudis. Kebanyakan warga tidak mandi pagi hari, kecuali beberapa orang membasuh muka dan gosok gigi. Rasa dingin membuat warga enggan mandi pagi hari.
Pada Senin 11 Agustus 2008 pukul 12.30, saya meninggalkan desa itu menuju pertigaan Mewet untuk mendapatkan ojek menuju Waiwerang, kemudian dari Waiwerang menggunakan perahu motor terus ke Larantuka. Perjalanan dilanjutkan ke Maumere untuk mendapatkan tiket pesawat yang setiap hari, pagi dan sore, ke Kupang.