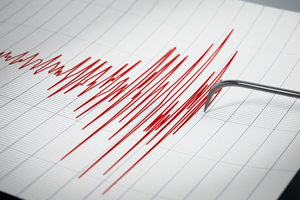Bisakah Program Deradikalisasi “Sembuhkan” Teroris?

KOMPAS.com -- Selama satu pekan terakhir, dunia telah digoncangkan dengan setidaknya tiga teror sekaligus. Pertama adalah ledakan bom saat konser Ariana Grande di Manchester, Inggris. Lalu, ada juga serangan di Marawi, Filipina Selatan. Terakhir, bom bunuh diri di Kampung Melayu menewaskan tiga anggota Polri.
Selain memukul mundur teroris secara fisik, negara-negara di dunia juga mulai menggalakkan program deradikalisasi untuk “menyembuhkan” teroris. Program-program ini biasanya menganggap ekstrimisme agama sebagai penyakit mental dan berisi konselor dan psikolog yang berusaha meyakinkan ekstremis agama bahwa pandangan mereka tidak memiliki dasar teologi yang tepat.
(Baca juga: Seperti Inilah Gambaran Otak Seorang Ekstremis Agama)
Walaupun ide tersebut terdengar meyakinkan, Daniel Koehler, direktur dari German Institute of Radicalization and De-radicalization Studies di Stuttgart, Jerman, berkata bahwa tidak ada bukti yang jelas mengenai keefektifan program-program tersebut.
Kepada Science 26 Mei 2017, Koehler berkata bahwa program-program deradikalisasi menjadi semakin populer di berbagai negara bukan karena adanya bukti yang pasti mengenai efektifitas mereka, tetapi karena kebutuhan dari masyarakat, pembuat kebijakan, dan pejabat keamanan.
“Kita bisa mengalahkan grup-grup seperti ISIS atau ekstrimis lainnya secara fisik, tetapi hal ini tidak menyentuh daya tarik mereka sama sekali atau bahkan malah memperkuatnya,” ujarnya.
Akan tetapi, Koehler memperingatkan bahwa penggunaan metode yang salah dalam program deradikalisasi bisa menjadi senjata makan tuan. Dia mengatakan, fakta bahwa orang tersebut berada dalam program deradikalisasi bisa membuat pejabat keamanan dan orang-orang di komunitasnya lengah, membutakan mereka terhadap bahaya dari orang tersebut.
Walaupun demikian, Koehler tidak serta-merta menganggap program deradikalisasi sebagai sesuatu yang sia-sia. Menurut dia, program ini bisa digunakan sebagai jembatan komunikasi antara pejabat keamanan, anggota keluarga teroris dan komunitas.
Dalam kasus bom di Manchester, misalnya, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa anggota keluarga dan teman pelaku telah mengetahui mengenai proses radikalisasi atau rencana penyerangan tersebut. Mereka juga telah berkali-kali menyampaikannya kepada pihak yang berwenang.
(Baca juga: Studi "Antropologi Tobat" Mengungkapkan Kisah di Balik Insafnya Para Ekstremis Islam)
“Mekanisme dasarnya sama: Anda butuh akses ke orang yang telah teradikalisasi, mengidentifikasikan faktor-faktor yang mendorong ideologi mereka, merencanakan intervensi, dan melacak dampaknya,” ucap Koehler.
Metode tersebut, menurut dia, dapat diaplikasikan ke semua jenis organisasi teroris. “Penelitian telah menunjukkan banyaknya kesamaan di balik motif seseorang untuk bergabung dan meninggalkan kelompok teroris,” katanya.
Dia melanjutkan, tentu tipe dan struktur program harus diadaptasikan untuk masing-masing individu dan keadaan, tetapi intinya adalah mengetahui ikatan orang tersebut terhadap kelompok teroris dan ideologinya sebelum menciptakan strategi keluar yang dirancang khusus untuk orang tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.